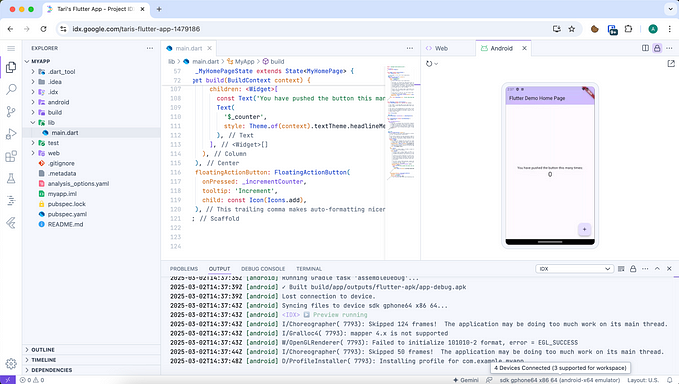Sejarah Kelam Praktik Objektifikasi Perempuan Gerwani Dalam Tragedi 1965
Windy Koesherawaty (Windwiniee)
Trigger warning: kekerasan seksual, penyiksaan seksual
Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) merupakan sebuah organisasi perempuan berhaluan sosialis-feminis yang cukup besar dan progresif di tahun 1965. Naas, gerakan progresif mereka harus terhenti ketika mereka dituding terlibat dalam pembunuhan kejam para jenderal pada 30 September 1965 di Lubang Buaya yang dikonstruksikan dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Padahal, Gerwani sama sekali tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut meskipun pada saat itu mereka erat bersekutu dengan PKI. Sebagai catatan awal, kendatipun pembunuhan tersebut sendiri sebenarnya juga tidak dilakukan oleh PKI, akan tetapi narasi ini secara khusus hanya akan membahas bagaimana tuduhan keterlibatan perempuan Gerwani saat itu dilakukan melalui berbagai fitnah-fitnah yang merendahkan martabat mereka sebagai perempuan.
Dalam narasi-narasi fitnah terhadap mereka, perempuan Gerwani dikatakan memiliki andil besar dalam penyiksaan dan pembunuhan para Jenderal berupa menari tanpa busana (naked) dan memotong kemaluan para jenderal. Menurut Wieringa (2022), narasi ini seolah mengkonstruksikan bahwa kehormatan laki-laki yang ‘termiliterisasi’ telah dicemarkan oleh para perempuan Gerwani. Sejak saat itu, kampanye fitnah seksual terhadap perempuan Gerwani secara masif terjadi di Indonesia hingga menimbulkan kemarahan besar di masyarakat. Menurut wawancara penulis dengan pengurus lembaga swadaya masyarakat bernama KontraS yang aktif mengadvokasi para penyintas ’65, perempuan Gerwani bahkan dikampanyekan sebagai seorang pelacur yang pantas dibunuh, digambarkan sebagai perempuan buruk rupa yang jahat, dan berbagai perumpamaan menyeramkan lainnya. Akibatnya, jutaan dari perempuan Gerwani dibunuh ataupun ditahan sebagai “tahanan politik” dalam penjara.
Namun, dibunuh ataupun ditahan saat itu pada dasarnya tampak tidak jauh berbeda. Bagi mereka yang dibunuh, tentu telah mengalami rentetan penyiksaan sebelumnya. Sementara itu bagi mereka yang ditahan, setiap harinya mereka harus mengalami rentetan penyiksaan, penindasan, penghinaan, dan lain sebagainya –seolah sedang dibunuh secara perlahan.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wieringa, ditemukan bahwa laki-laki yang turut menjadi tahanan politik bahkan dipaksa untuk menyaksikan interogasi kepada perempuan Gerwani. Lebih tepatnya, interogasi yang diiringi tindakan tidak manusiawi seperti memaksa perempuan Gerwani membuka busana untuk kemudian difoto dan dijadikan bukti palsu atas tuduhan “menari telanjang” selama pembunuhan para jenderal, memasukan gagang cambuk ke vagina perempuan Gerwani, memperkosa mereka, mengikat leher mereka dengan tali, memaksa mereka bersetubuh dengan kawat listrik yang ditempelkan pada vagina mereka, memasukan botol-botol ke dalam vagina mereka, serta lain sebagainya. Di hari-hari setelah interogasi, praktik tindakan tidak manusiawi yang jauh lebih buruk terus dialami oleh perempuan Gerwani bak sebuah kewajiban yang tidak boleh terlewatkan.
Anehnya, praktik penyiksaan tidak dialami sedemikian rupa oleh laki-laki yang menjadi tahanan politik. Meskipun terdapat beberapa bukti kasus bahwa laki-laki pernah disasar secara seksual seperti dipotong penisnya, tetapi kasus tersebut terbilang jauh lebih sedikit daripada jumlah kekerasan dan penyiksaan seksual yang dialami oleh hampir seluruh perempuan Gerwani saat itu. Hal ini semakin mempertegas premis bahwa segala praktik penghukuman yang diberikan kepada perempuan Gerwani saat itu seolah menjadi “celah” bagi para laki-laki untuk meluapkan nafsu mereka dengan dalih amarah terhadap PKI.
Dalam perspektif feminis, jelas bahwa fenomena tersebut menunjukan adanya bentuk penempatan perempuan sebagai “objek” pemuas seksual laki-laki yang telah membudaya, bersamaan dengan sistem patriarki yang membuat laki-laki merasa memiliki hak sepihak untuk menindas perempuan (Gerassi, L, 2015).
Penindasan-penindasan yang dialami oleh perempuan Gerwani tersebut terus berlangsung selama belasan tahun. Sampai akhirnya sejak tahun 1977 hingga 1979 mereka yang dirasa cukup “dibina” mulai dibebaskan. Sementara yang masih dianggap belum “bersih” dan “bebas” dari ajaran komunis harus tetap menjalani penahanan di tempat-tempat penahanan lain (Ardanareswari & Teguh, 2019). Akan tetapi, bebas dari penjara pun belum berarti perempuan Gerwani dapat kembali merdeka menjalankan kehidupannya. Hal ini karena di tahun-tahun setelahnya mereka harus terus distigmakan sebagai perempuan yang buruk dan pantas untuk dibenci masyarakat. Belum lagi, pemerintah di era kebrutalan represi Soeharto juga turut memanipulasi kesadaran kolektif masyarakat Indonesia melalui propaganda yang kian mengkonstruksikan citra buruk perempuan Gerwani. Akibatnya, hingga pasca hampir 60 tahun tragedi tersebut terjadi, kini masih terdapat gap antara pengetahuan umum masyarakat dengan realita yang terjadi sebenarnya.
Menurut Sahlins (1985) dalam Insani, H. R., & Irwandi, A (2022), peristiwa sejarah sejatinya ditentukan oleh budaya yang mengkonstruksikan bagaimana “kebenaran” di masa lalu.
Dalam hal ini, maka jelas bahwa budaya objektifikasi perempuan dan patriarki di masyarakat saat itu melihat bahwa penindasan terhadap perempuan Gerwani adalah suatu kebenaran. Lebih lanjut, budaya tersebut dikombinasikan dengan pengaruh kepentingan dan kekuasaan negara yang kemudian memperkuat kebenaran tersebut hingga menciptakan gap pengetahuan sejarah di masyarakat dengan realita yang terjadi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bagaimanapun kebencian dan ketakutan terhadap PKI, tetapi tanpa propaganda dusta pemerintah maka tindakan tidak manusiawi terhadap perempuan Gerwani tidak akan terjadi.
Pada titik ini, maka sejatinya penting untuk lebih dalam menguak fenomena ini dengan metode etnohistoris yang berpusat pada upaya untuk merekonstruksi sejarah dan membuka realita yang sebenarnya. Melalui metode etnohistoris, nantinya akan diketahui bagaimana penindasan perempuan Gerwani dan propaganda rezim Soeharto pada akhirnya akan menghasilkan benang merah yang merujuk kepada praktik objektifikasi perempuan, patriarki, dan upaya untuk menundukan perempuan.
Untuk dapat memahami narasi ini secara lebih mendalam, pada halaman berikutnya akan terdapat sebuah esai visual yang secara runut menjelaskan bagaimana kerangka berpikir dari narasi ini.





Referensi:
Ardanareswari, I., & Teguh, I. (2019, October 7). Bagaimana nasib Gerwani Setelah G30S? Tirto.Id. Insani, H. R., & Irwandi, A. (2022). Kejayaan Rempah Dari Pulau Kei Raha: Pandangan Etnohistori. Balale’: Jurnal Antropologi, 3(1).
Yayatmaka, Y, et al. (2016). Sejarah gerakan kiri Indonesia: Untuk pemula. Ultimus.
Wieringa, S. (2002). Sexual politics in Indonesia. Springer.